Buat saya sederhana saja: orang pintar itu membuat orang lain mudah untuk menjadi pintar juga. Orang pintar itu akan terlihat dari kemampuannya untuk mengutarakan pikirannya secara sederhana pada orang lain. Tulisan yang mudah dipahami menunjukkan kualitas dan kedalaman pemahaman penulisnya. Bacalah tulisan Anthony Giddens, atau Arief Budiman, dan Anda akan tahu apa yang saya maksud.
Berdasarkan standarisasi semacam itulah, tempo hari Graham Fuller ‘mengambil hati’ saya lewat bukunya The future of political Islam (2003). Di sana ia bertutur dengan renyah, seperti mengajak pembaca berbincang tentang gagasannya mengenai wajah Islam politik di masa depan. Saya suka cara Fuller menawarkan gagasan dan pikirannya. Dengan cara yang sama, artikelnya yang berjudul ‘A world without Islam’ (Foreign Policy, 2008) juga sangat bernas menawarkan cara pandang yang menarik. Karena itulah, ketika mengetahui bahwa Fuller menerbitkan lagi sebuah buku berjudul persis sama seperti artikel tersebut (A world without Islam, 2010) saya segera yakin bahwa buku ini pasti menarik. Sayangnya butuh waktu hingga 3 bulan bagi saya untuk menyentuh buku itu sejak memesannya di Amazon bulan Nopember lalu.
Buku setebal 328 halaman ini, seperti saya duga sejak awal, segera menyita perhatian dan waktu saya sejak membuka lembar awalnya. Penyebab pertama adalah gaya penulisan yang sangat bertutur, dan di beberapa titik cukup profokatif. Penyebab kedua adalah perspektif yang disajikan Fuller, seorang mantan Wakil Ketua National Intelligence Council di CIA, yang membuat orang seperti saya cenderung merasa nyaman. Yang saya maksud dengan frase “orang seperti saya” adalah orang yang selalu dibuat gundah oleh cara berpikir sangat stereotype tentang orang atau kelompok lain dalam masyarakat yang sangat majemuk.

Marilah saya ambil contoh. Suatu hari di depan Istana Merdeka, sekelompok orang berunjuk-rasa menuntut pembubaran Ahmadiyah. Mereka membawa sebuah spanduk besar berisi wajah sejumlah tokoh termasuk Mirza Ghulam Ahmad dan beberapa orang yang dianggap melindungi keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Yang menarik, di sela gambar-gambar wajah itu terdapat simbol bintang Daud berwarna biru. Pesan yang ingin disampaikan oleh gambar itu amat jelas: Yahudi berperan di balik semua ini.
Apakah benar Yahudi berada di balik semua ini sangatlah bisa diperdebatkan. Namun kejadian ini jelas menggambarkan cara pikir yang sangat stereotype tentang Yahudi. Bagi sejumlah orang (di Indonesia) Yahudi adalah kambing hitam sejumlah besar persoalan. Kejadian politik yang pelik seringkali diberi penjelasan mudah dan lekas: ‘itu adalah konspirasi Yahudi’. Benar atau tidak, itu urusan lain.
Jika di Indonesia jalan berpikir yang sangat stereotype itu menjadikan Yahudi sebagai pangkal segala persoalan, maka pada skala global Islam lah yang menjadi juaranya. Semenjak peristiwa 911, opini publik di negara-negara superpower secara sistematis terbentuk untuk menempatkan Islam dan Muslim dalam gambaran buruk sebagai teroris atau orang-orang yang tak segan menyakiti bahkan membunuh orang lain yang berbeda keyakinan. Selama beberapa tahun tinggal di Australia, saya merasakan betul bahwa cukup banyak orang awam yang memiliki jalan berpikir semacam ini. Terlepas dari kenyataan bahwa memang ada sejumlah kecil Muslim yang menggemari kekerasan atas nama agama, gambaran stereotyping ini jelas-jelas salah arah dan membuat gusar.
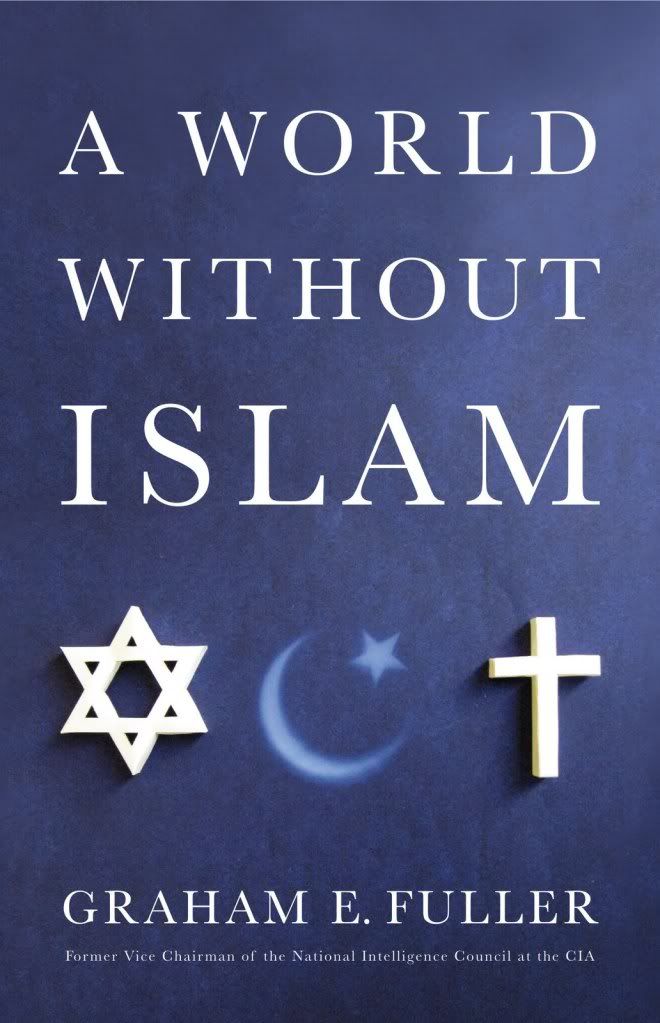 Kepada orang dengan cara berpikir seperti inilah buku Fuller ini layak untuk disarankan. Persis sama seperti dalam tulisan di tahun 2008, dalam buku ini pun Fuller memulai diskusi dengan kalimat yang cukup provokatif: “Imagine, if you will, a world without Islam.” Seperti apa wajah dunia jika tak ada Islam? Demikian Fuller mengajak pembaca berandai-andai. Sejumlah orang mungkin yakin bahwa tanpa Islam, tak akan ada perbenturan peradaban seperti yang digambarkan Huntington (1993, 1996), tak ada perang jihad, tak ada terorisme. Tapi Fuller menolak asumsi itu. Ia sejak awal meyakinkan pembaca bahwa andai Islam dihapus dari jejak sejarah, maka wajah dunia tetap akan sama seperti yang kita lihat sekarang.
Kepada orang dengan cara berpikir seperti inilah buku Fuller ini layak untuk disarankan. Persis sama seperti dalam tulisan di tahun 2008, dalam buku ini pun Fuller memulai diskusi dengan kalimat yang cukup provokatif: “Imagine, if you will, a world without Islam.” Seperti apa wajah dunia jika tak ada Islam? Demikian Fuller mengajak pembaca berandai-andai. Sejumlah orang mungkin yakin bahwa tanpa Islam, tak akan ada perbenturan peradaban seperti yang digambarkan Huntington (1993, 1996), tak ada perang jihad, tak ada terorisme. Tapi Fuller menolak asumsi itu. Ia sejak awal meyakinkan pembaca bahwa andai Islam dihapus dari jejak sejarah, maka wajah dunia tetap akan sama seperti yang kita lihat sekarang.
Sepanjang 14 bab buku ini, Fuller secara terinci memaparkan argumen tersebut dalam 3 (tiga) bagian besar. Bagian pertama mengajak kita untuk melihat akar, keterkaitan dan sejarah ketegangan Islam dan Kristen. Ia memulai bagian ini dengan melongok ke ajaran babon ketiga agama besar (Yahudi, Kristen dan Islam), yakni ajaran Ibrahim tenang monoteisme. Di bab pertama yang berbicara tentang ajaran Ibrahim ini, Fuller mengutip ayat ketiga surah Al Ikhlas dalam terjemahan Bahasa Inggris: “God neither begets, nor is He begotten.” Bagian kedua memetakan relasi antara Islam dan peradaban lain khususnya Barat, Rusia Ortodox, India dan Cina. Fuller menggambarkan hubungan antar peradaban yang (sebenarnya) lebih didominasi oleh relasi saling menguntungkan, ketimbang konflik dan konfrontasi. Di bagian ketiga, Fuller mengajak kita untuk melihat sejarah yang lebih terkini dalam hubungan Barat dan Islam. Hubungan ini banyak ditentukan oleh kolonialisme, tumbuhnya nasionalisme, dan perjuangan kemerdekaan. Tentu saja ada warna-warna konflik yang muncul belakangan, terlebih satu dekade terakhir, ketika tarikan kepentingan politik dan ekonomi tenggelam dalam tema-tema keagamaan yang sangat kuat. Di era ini tema kebangsaan dan geopolitik jadi tak semenonjol tema keagamaan seperti jihad.
Tak ada yang baru dengan semua data yang disajikan di sini. Sejarah agama-agama dan relasinya satu sama lain telah banyak dibahas oleh para begawan seperti Karen Armstrong (1993) atau Ira Lapidus (1988). Peta terkini dalam hubungan Barat dan Islam telah secara mengesankan dibahas oleh Bernard Lewis (2002).
Kontribusi utama Fuller dalam diskusi ini adalah perspektifnya. Tekanan utama yang dibuat oleh Fuller adalah bahwa faktor geopolitik lebih banyak menentukan pola relasi Barat dan Islam, ketimbang isu agama. Tentu saja para pengkaji Timur Tengah dan Islam telah sangat lama mengingatkan pentingnya untuk memahami setting sejarah dan geopolitik dalam konflik Barat dan Islam. Bernard Lewis, misalnya, banyak membahas ini dalam sejumlah karyanya (1990, 1993, 2002). Namun Fuller menekannya secara lebih eksplisit dalam buku ini. Fuller menulis:
[D]eeper geopolitical factors have created numerous confrontational factors between the East and the West that predate Islam, continued with Islam and around Islam, and may be inherent in the territorial imperatives and geopolitical outlook of any states that occupy those areas, regardless of religion. (p. 5)
Untuk memahami bagaimana faktor geopolitik jauh lebih menentukan ketimbang faktor keagamaan, Fuller mengajak pembaca untuk melihat banyaknya kesamaan isu antara konflik Ortodoks vs Katolik, dan konflik Islam vs Kristen. Dua-duanya terpola menurut peta Barat dan Timur. Masalahnya, tegas Fuller, orang Barat seringkali lemot kalau sudah berurusan dengan isu-isu nasionalisme dan identitas (terlebih dalam kasus Timur Tengah), dan mau ambil gampang dengan melempar semua permasalahan ke keranjang “Islam”. Pokoknya, ada masalah apapun pasti gara-gara Islam yang anti Kristen dan Barat.
Untuk itu, ada dua ajakan penting Fuller yang perlu digaris-bawahi. Fuller mengingatkan pada publik Barat bahwa Islam adalah bagian yang integral dan sangat kompleks dari pengalaman bersama seluruh ummat manusia dalam hal kemanusiaan, politik dan keagamaan. Jika ada masalah dalam Islam, itu adalah masalah seluruh ummat manusia dan relasi antar mereka. Dalam hal ini Fuller mengingatkan lagi bahwa meskipun ada satu Islam, namun terdapat banyak ragam dalam cara ummat Islam menafsirkan dan mempraktekkan ajaran agama yang satu itu. Penting untuk diingat bahwa penekanan tentang komunitas Islam yang tidak ‘tunggal’ sering dilakukan oleh banyak peneliti, termasuk oleh Bernard Lewis (1990) serta Anthony Bubalo dan Greg Fealey (2005). Menurut saya, ummat Islam sendiri pun perlu terus merenungi dan belajar memahami kenyataan bahwa terdapat keragaman dalam dirinya. Dalam aspek ini masih banyak kaum Muslimin yang belepotan.
Ajakan lain yang juga penting yang dilontarkan Fuller (betapapun normatifnya) adalah untuk terus mendorong kerukunan beragama, khususnya antara para penganut ajaran Ibrahim. Jika kita familiar dengan ajakan almarhum Nurcholish Madjid tentang kalimah sawa’ (Madjid 1992), maka kita tak akan asing dengan substansi ajakan Fuller berikut ini, yang konsisten dengan idenya tentang faktor geopolitik di atas.
[W]e are hopefully working toward building a solid foundation for the three great Abrahamic faiths … that shares more they dispute. It is the states that dispute.
(p. 16)
Setujukah Anda dengan ajakan itu? Terserah Anda. Allahu a’lam bissawab. Yang penting: selamat membaca.[]
——————————————————————————
Judul Buku: A World Without Islam
Penulis: Graham E. Fuller
Penerbit: Little, Brown and Company (New York)
Tahun: 2010
Tebal: viii + 328 halaman
——————————————————————————
Rujukan
Armstrong, K. (1993). A history of God: the 4,000-year quest of Judaism, Christianity and Islam. New York: Random House.
Bubalo, A., & Fealy, G. (2005). Joining the caravan? the Middle East, Islamism and Indonesia. New South Wales: Longueville Media.
Fuller, G. E. (2003). The future of political Islam. New York: Palgrave Macmillan.
Fuller, G. E. (2008). ‘A world without Islam.’ Foreign Policy, Jan-Feb. (Bisa diakses di http://www.foreignpolicy.com/articles/2007/12/13/a_world_without_islam).
Fuller, G. E. (2010). A world without Islam. New York: Little, Brown and Company.
Huntington, S. P. (1993). ‘The clash of civilization?’ Foreign Affairs, 72(3), 22-49.
Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster.
Lapidus, I. M. (1988). A history of Islamic societies. Cambridge: Cambridge University Press.
Lewis, B. (1990). ‘The roots of Muslim rage’. The Atlantic, 266(3), 47-60. (Bisa diakses di http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1990/09/the-roots-of-muslim-rage/4643/).
Lewis, B. (1993). Islam and the West. New York: Oxford University Press.
Lewis, B. (2002). What went wrong: Western impact and Middle Eastern response. New York: Oxford University Press.
Madjid, N. (1992). Islam: doktrin dan peradaban. Jakarta: Paramadina.